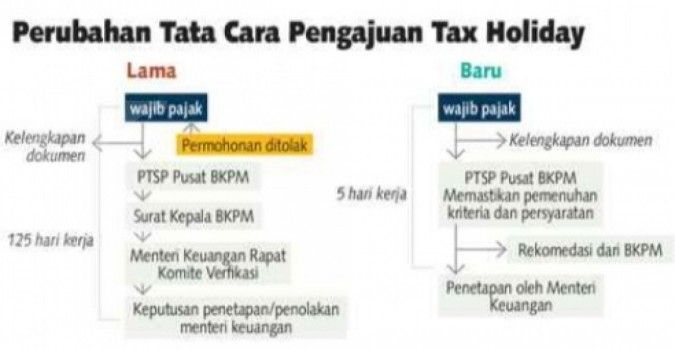Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Layanan jasa digital alias Over-The-Top (OTT) merupakan salah satu sektor ekonomi digital yang bertumbuh pesat, terutama di Indonesia. Lantas, potensi penerimaan pajak dari sektor ini pun begitu besar dan patut direspon se-efektif mungkin.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pernah mencatat, Indonesia berkontribusi sekitar Rp 15 triliun terhadap pasar OTT global per tahunnya. Sayang, kompleksitas OTT membuat aturan dan kebijakan pajak sektor ini sulit dibuat tak hanya di Indonesia, melainkan di berbagai negara di dunia.
Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), mengatakan, penerapan PPh atau pengenalan jenis pajak baru untuk OTT terus menjadi polemik secara global.
"Soalnya, hak pemajakan lintas negara (PPh) masih berpatokan pada keberadaan fisik padahal praktik bisnisnya sudah tidak mensyaratkan demikian," ujar Yustinus, Kamis (25/10).
Setelah melakukan kajian komparatif, Yustinus mengemukakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jasa digital cross-border bisa menjadi solusi untuk menjaring penerimaan tanpa mengubah sistem yang ada.
Asal tahu saja, PPN menganut prinsip destinasi (destination principle), yaitu pajak dikenakan pada tempat di mana barang atau jasa tersebut dikonsumsi atau negara sumber penghasilan (source-income country).
CITA melihat, aktivitas OTT jelas memenuhi syarat sebagai transaksi yang terutang PPN. "Selain itu, sudah ada acuannya juga dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), ada best practice dari beberapa negara lain, dan secara legal administratif juga memungkinkan," kata Yustinus.
Mekanisme yang diterapkan antara lain ialah supplier collection, yakni tugas pemungutan PPN dilakukan oleh supplier asing. Secara teknis, supplier dengan omset melebihi threshold Rp 4,8 miliar diwajibkan melakukan registrasi sebagai pemungut PPN.
Nantinya, Yustinus menjelaskan, PPN yang terkumpul disetor dan dilaporkan dalam periode tertentu melalui mekanisme sederhana (simplified registration), tanpa perlu dalam format full-reporting.
Memang, Yustinus bilang, untuk menerapkan supplier collection perlu revisi UU PPN Pasal 3A ayat 3 yang substansinya mengatur pendekatan consumer collection. Pasal 2 UU KUP yang mengatur tempat dan syarat pendaftaran juga menjadi tidak relevan.
"Reformasi pajak bisa jadi momentum tepat untuk memperbaiki kerangka hukum dan aturan teknis pemajakan ekonomi digital," terangnya.
Lebih lanjut, Yustinus menjelaskan, skema supplier collection ini hanya berlaku untuk transaksi business-to-customer (B2C). Transaksi yang bersifat business-to-business (B2B) tetap mengikuti perundang-undangan melalui pemungutan PPN atas impor jasa luar negeri terhadap pengusaha kena pajak (PKP) atau dikenal juga dengan reverse charge.
Mekanisme supplier collection tersebut, menurut Yustinus, cukup populer lantaran sebanyak 29 dari 35 negara OECD telah mengadopsinya. Begitu juga dengan Uni Eropa, Rusia, India, dan Afrika Selatan.
Adapun, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Rofyanto Kurniawan, mengakui penerapan skema PPN untuk pasar OTT tersebut mungkin saja diterapkan di Indonesia. BKF sendiri telah mempelajari penerapan pajak ekonomi digital sejumlah negara, seperti Uni Eropa dan Australia.
"Kami juga prinsipnya, tidak ada jenis pajak baru untuk ekonomi digital dan mengupayakan same level playing field untuk pelaku bisnis digital maupun konvensional," tandas Rofyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


/2017/02/17/123042919.jpg)