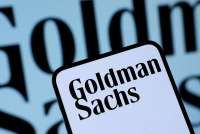Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Swasembada pangan menjadi salah satu poin dalam Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, program ini dinilai tak sesuai dengan realita kondisi Indonesia.
Guru Besar IPB University Prof. Dwi Andreas Santosa menjelaskan, konsep swasembada pangan atau food self-sufficiency hanya dapat dicapai ketika rasio antara produksi dan konsumsi (self-sufficiency ratio) sama atau lebih besar dari satu. Artinya, produksi harus setara atau melampaui konsumsi nasional.
“Jika melihat impor 12 komoditas pangan utama yang justru melonjak dari 22 juta ton menjadi 34 juta ton dalam sepuluh tahun terakhir, swasembada pangan nasional jelas mustahil,” ungkap Andreas kepada Kontan, Sabtu (18/10/2025).
Lagipula, ada sejumlah komoditas yang tak bisa diproduksi Indonesia. Sebut saja gandum yang rata-rata impornya mencapai 11 juta ton per tahun. Kondisi agroklimat Indonesia yang tidak mendukung budidaya gandum membuat komoditas ini jelas sulit digantikan dengan produksi dalam negeri.
Oleh karenanya, Andreas menilai pemerintah perlu mereduksi target menjadi swasembada pada komoditas tertentu, seperti beras atau jagung, ketimbang memaksakan swasembada pangan secara total.
Baca Juga: YLKI Beri Rapor Merah Sektor Pangan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo–Gibran
Toh, capaian produksi beras nasional pada 2025 meningkat signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan capaian itu, pemerintah bakal mengumumkan swasembada beras penuh tahun 2025.
Pun, itu bukan hal baru, mengingat Indonesia juga pernah tak mengimpor beras konsumsi selama empat tahun berturut-turut pada 2019–2022.
Nah, Andreas mengingatkan agar pencapaian tahun ini tak sekadar menjadi sebuah pencapaian, tetapi menjadi kondisi yang berkelanjutan. Pasalnya, peningkatan produksi tahun ini banyak ditopang oleh faktor alam, yakni kemarau basah yang menyebabkan intensitas hujan tinggi sepanjang tahun.
Kondisi itu memperluas area tanam dan panen, sehingga memungkinkan produksi meningkat sekitar 12% dibanding tahun sebelumnya. Namun, jika pada 2026 terjadi El Nino atau kemarau panjang, hasil produksi bisa saja kembali menurun.
Selain cuaca, ancaman lain datang dari potensi serangan hama seperti yang terjadi pada 2017, ketika produksi anjlok setelah peningkatan tajam di tahun sebelumnya. Andreas menilai pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan pola serupa terulang dan menyiapkan strategi pengendalian hama sejak dini agar tidak terjadi lonjakan impor pada tahun berikutnya.
Baca Juga: Usai Sertijab Jadi Kepala Bapanas, Amran Bakal Pelototi Rp 150 Triliun Subsidi Pangan
Food estate
Andreas juga menyoroti pendekatan pemerintah yang kembali mendorong proyek food estate atau pembukaan lahan skala besar, meski telah terbukti gagal dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya terlibat dalam pembukaan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah tahun 1996–1998. Apa yang terjadi saat itu? Gagal semua,” ungkap Andreas.
Food estate yang sudah terbukti gagal itu, baik secara ekonomi maupun ekologis, bahkan menjadi salah satu pusat kebakaran hutan besar pada 2015, dengan kerugian yang ditaksir mencapai US$ 16 miliar.
Menurutnya, hampir seluruh proyek serupa, mulai dari MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) pada era SBY hingga food estate di masa Jokowi yang juga berlokasi di Merauke, berakhir gagal karena mengabaikan prinsip ilmiah kelayakan lahan.
Ia menegaskan, selama empat pilar pengembangan pertanian skala luas tidak terpenuhi, hasilnya akan selalu sama. Empat pilar yang dimaksud yaitu kesesuaian atau kelayakan tanah dan agroklimat, kesesuaian infrastruktur, kelayakan budidaya dan teknologi, serta kelayakan sosial-ekonomi.
Baca Juga: Menteri Amran Pastikan RI Swasembada Beras Dua hingga Tiga Bulan Lagi
Alih-alih food estate, Andreas menyarankan agar pemerintah mengalihkan fokus pada peningkatan produktivitas lahan eksisting.
Ia membeberkan bahwa produktivitas padi Indonesia saat ini stagnan di kisaran 5,1 ton hingga 5,3 ton per hektare, bahkan menurun sekitar 0,7% per tahun selama satu dekade terakhir.
Sebagai perbandingan, Vietnam malah sudah mencapai 6–6,2 ton per hektare. Padahal, varietas padi unggul Indonesia memiliki potensi hasil di atas 10 ton per hektare jika dikelola optimal.
Andreas menilai peningkatan produktivitas dan adaptasi terhadap variabilitas iklim merupakan kunci utama memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Siapapun yang memerintah, sebaiknya fokus ke produktivitas. Tidak perlu buka lahan baru, dana disebarkan ke sana ke mari,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


/2025/06/23/1513895167.jpg)