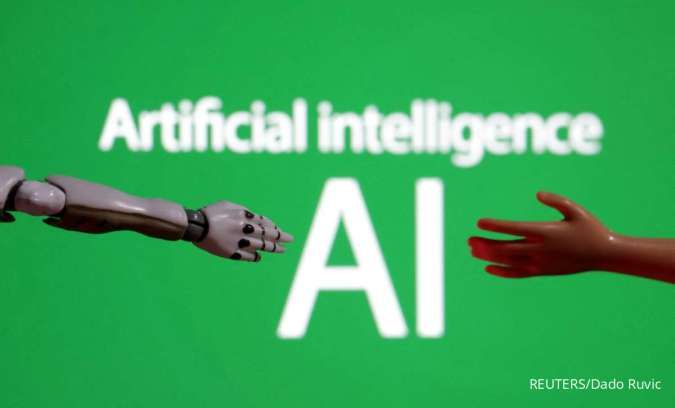Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini
KONTAN.CO.ID - Perdebatan mengenai penetapan status “bencana nasional” kembali menguat setiap kali terjadi krisis berskala besar. Namun dalam banyak diskusi publik, isu ini kerap bergeser dari ranah kebencanaan ke ranah politisasi. Narasi yang muncul seolah-olah keputusan mengenai status tersebut sepenuhnya bergantung pada kehendak politik pemerintah pusat. Penyederhanaan seperti ini tidak hanya mengaburkan substansi, tetapi juga menyesatkan publik dalam memahami cara negara bekerja ketika sebuah bencana terjadi.
Status bencana nasional bukan instrumen politis. Ia lahir dari mekanisme hukum dengan indikator objektif: runtuh atau tidak berfungsinya struktur pemerintahan daerah untuk menjalankan komando darurat, mengoordinasikan layanan, dan memastikan keberlanjutan pelayanan publik. Selama pemerintah daerah masih memegang kendali, meski dalam kondisi tertekan, status nasional tidak dapat diberlakukan. Kerangka ini dibuat bukan untuk menghambat respons negara, tetapi untuk menjaga rasionalitas tata kelola dalam situasi krisis.
Kesalahpahaman sering muncul karena ada anggapan bahwa semakin tinggi status yang disematkan, semakin serius pula perhatian pemerintah pusat. Padahal, respons pusat sama sekali tidak bergantung pada label administratif tersebut. Respons cepat kementerian dan lembaga. Mulai dari TNI, Polri, BNPB, PLN, hingga kementerian teknis—menunjukkan bahwa urgensi lapanganlah yang menggerakkan negara, bukan status hukum yang tertera dalam dokumen. Menempatkan status sebagai ukuran kepedulian justru menyederhanakan kerja teknis yang sudah dilakukan sejak hari pertama.
Dinamika media sosial memperumit situasi ini. Tekanan agar bencana segera “dinasionalkan” kerap lahir dari kecenderungan empathy signaling, sebuah dorongan untuk menunjukkan kepedulian secara cepat dan publik yang tidak selalu diiringi pemahaman terhadap parameter regulatif. Empati jelas diperlukan dalam sebuah krisis, tetapi tanpa literasi yang memadai, empati dapat berubah menjadi tuntutan emosional yang tidak selaras dengan arsitektur hukum penanggulangan bencana. Instrumen kebijakan negara tidak dapat berjalan mengikuti intensitas percakapan digital.
Di tengah hiruk pikuk tuntutan publik, prinsip otonomi daerah sering kali terabaikan. Sistem kebencanaan Indonesia dibangun dengan mekanisme bertingkat: kabupaten/kota sebagai aktor pertama, provinsi sebagai penguat, dan pusat sebagai intervensi tertinggi ketika kapasitas daerah runtuh. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip subsidiarity yang menempatkan keputusan sedekat mungkin dengan titik krisis. Mengambil alih kewenangan daerah tanpa indikator yang sah bukan hanya bertentangan dengan kerangka desentralisasi, tetapi juga berisiko menimbulkan preseden yang merusak hubungan pusat–daerah dalam jangka panjang.
Kecenderungan untuk meminta pusat mengambil alih segala hal bukan hanya refleksi dari ketidaktahuan, tetapi juga berpotensi menjadi alat politisasi. Pemerintah daerah bisa dilabeli tidak mampu, sementara pemerintah pusat dapat didorong untuk bertindak di luar batas regulatifnya. Jika pola ini dibiarkan, maka isu kemanusiaan berubah menjadi arena delegitimasi politik. Sebaliknya, memperkuat kapasitas daerah dan menghormati struktur kewenangan yang ada justru sejalan dengan reformasi kebencanaan yang telah dibangun selama dua dekade terakhir.
Stratifikasi bencana seharusnya tidak menjadi ajang adu narasi. Yang diperlukan adalah kolaborasi yang proporsional antara pusat dan daerah, kepatuhan pada prinsip-prinsip tata kelola, serta peningkatan literasi publik agar dinamika informasi tidak terseret pada politisasi. Status bencana nasional bukan simbol kepedulian, bukan pula arena kompetisi politik; ia adalah keputusan hukum yang harus dijaga rasionalitasnya demi menghindari kekacauan komando dalam situasi darurat.
Di tengah krisis, negara memang harus bergerak cepat. Namun kecepatan tanpa kerangka hukum yang tepat justru membuka ruang bagi manipulasi politik dan kerentanan tata kelola. Otonomi daerah bukan hambatan, melainkan fondasi. Dan menjaga fondasi itu, terutama di tengah tekanan emosional publik, adalah bagian penting dari ketahanan demokrasi sekaligus ketahanan kebencanaan kita. 
Selanjutnya: Prabowo Pastikan Listrik di Lokasi Banjir Sumatra Akan Pulih Sebentar Lagi
Menarik Dibaca: Promo Tiket Nonton Agak Laen Menyala Pantiku di CGV & XXI Pakai BCA, Ada Cashback 50%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


/2025/12/01/1364809225.jpg)